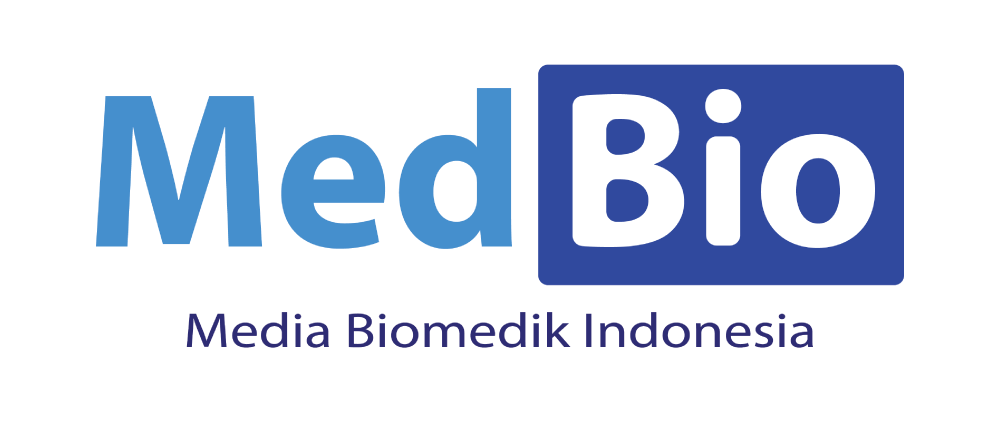Anemia artinya “kurang darah” didefinisikan sebagai penurunan jumlah total hemoglobin atau jumlah sel darah merah yang menyebabkan pasokan oksigen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh (Arulprakash & Umaiorubahan, 2018). Hemoglobin adalah suatu metaloprotein yaitu protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru keseluruh tubuh (Fitriany & Saputri, 2018).
Penyebab
anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya kekurangan asupan gizi, penyakit infeksi seperti malaria, mengalami perdarahan saat melahirkan, kebutuhan tubuh yang meningkat, akibat mengidap penyakit kronis, dan kehilangan darah akibat menstruasi dan infeksi parasite (cacing). (Kemenkes, 2019)
Epidemiologi
Prevalensi anemia berdasarkan World Health Organization (WHO) dari data yang dikumpulkan tahun 1993 hingga 2005 diperkirakan sekitar 1,6 miliar orang (seperempat dari populasi dunia) menderita anemia (Petry et al., 2016).
Prevalensi anemia di Indonesia masih cukup tinggi hasil menunjukkan bahwa angka prevalensi anemia secara nasional pada semua kelompok umur adalah 21,70 %(Priyanto, 2018). Sedangkan prevalensi anemia di Provinsi Jawa Timur sebesar 5,8 %. Angka tersebut masih dibawah target nasional yaitu sebesar 28%. WHO mengklasifikasi prevalensi anemia suatu daerah berdasarkan tingkat masalah yaitu berat ≥ 40 %, sedang 20%-39,9 %, ringan 5 % – 19,9 % dan normal ≤ 4,9 % (Natalia, Sumarmi, & Nadhiroh, 2018).
Patofisiologi
Patofisiologi anemia defisiensi besi (ADB) disebabkan karena gangguan homeostasis zat besi dalam tubuh. Homeostasis zat besi dalam tubuh diatur oleh penyerapan besi yang dipengaruhi asupan besi dan hilangnya zat besi/iron loss. Kurangnya asupan zat besi/iron intake, penurunan penyerapan, dan peningkatan hilangnya zat besi dapat menyebabkan ketidakseimbangan zat besi dalam tubuh sehingga menimbulkan anemia karena defisiensi besi. Zat besi yang diserap di bagian proksimal usus halus dan dapat dialirkan dalam darah bersama hemoglobin, masuk ke dalam enterosit, atau disimpan dalam bentuk ferritin dan transferin. Terdapat 3 jalur yang berperan dalam penyerapan besi, yaitu: (1) jalur heme, (2) jalur fero (Fe2+), dan (3) jalur feri (Fe3+). Zat besi tersedia dalam bentuk ion fero dan dan ion feri. Ion feri akan memasuki sel melalui jalur integrin-mobili ferrin (IMP), sedangkan ion fero memasuki sel dengan bantuan transporter metal divalent/divalent 15 metal transporter (DMT)-1. Zat besi yang berhasil masuk ke dalam enterosit akan berinteraksi dengan paraferitin untuk kemudian diabsropsi dan digunakan dalam proses eritropioesis. Sebagian lainnya dialirkan ke dalam plasma darah untuk reutilisasi atau disimpan dalam bentuk ferritin maupun berikatan dengan transferin. Kompleks besi-transferrin disimpan di dalam sel diluar sistem pencernaan atau berada di dalam darah. Transport transferrin dalam tubuh masih belum diketahui dengan pasti. Kapisitas dan afinitas transferin terhadap zat besi dipengaruhi oleh homeostasis dan kebutuhan zat besi dalam tubuh. Kelebihan zat besi lainnya kemudian dikeluarkan melalui keringat ataupun dihancurkan bersama sel darah. Perdarahan baik makro ataupun mikro adalah penyebab utama hilangnya zat besi. Sering kali perdarahan yang bersifat mikro atau okulta tidak disadari dan berlangsung kronis, sehingga menyebabkan zat besi ikut terbuang dalam darah dan lama-kelamaan menyebabkan cadangan zat besi dalam tubuh ikut terbuang. Keadan-keadaan seperti penyakit Celiac, postoperasi gastrointestinal yang mengganggu mukosa dan vili pada usus, sehingga penyerapan besi terganggu dan menyebabkan homeostasis zat besi juga terganggu.
Manifestasi klinis
anemia dapat mengakibatkan gangguan ataupun hambatan pada pertumbuhan sel tubuh maupun sel otak. Kurangnya kadar hemoglobin dalam darah dapat menimbulkan gejala
Gejala anemia sering disebut dengan 5L (lesu, letih, lemah, lelah, lalai) disertai dengan pusing kepala terasa berputar, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, serta sulit konsentrasi karena kurangnya kadar oksigen dalam otak.
Komplikasi
Penderita anemia yang tidak mendapat perawatan yang baik bisa saja mengalami beberapa komplikasi seperti kesulitan melakukan aktivitas akibat mudah lelah. Masalah pada jantung, seperti aritmia dan gagal jantung. Gangguan pada paru misalnya hipertensi pulmonal. Selain itu anemia juga dapat memicu terjadinya komplikasi kehamilan, seperti melahirkan prematur, atau bayi terlahir dengan berat badan rendah serta resiko kematian akibat perdarahan saat melahirkan. Penderita anemia juga 17 rentan mengalami infeksi dan akan terjadi gangguan tumbuh kembang apabila terjadi pada anak-anak atau bayi (Josephine D, 2020).
Penatalaksanaan
Anemia dapat dicegah dengan konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C dan Zink, dan pemberian tablet tambah darah (Kemenkes RI, 2018).
Sedangkan menurut Amalia A, dan Agustyas, 2016 tatalaksana anemia ada 3 yakni,
1) Pemberian Zat besi oral
2) Pemberian Zat besi intramuscular. Terapi ini dipertimbangkan apabila respon pemberian zat besi secara oral tidak berjalan baik.
3) Transfusi darah diberikan apabila gejala anemia disertai dengan adanya resiko gagal jantung yakni ketika kadar Hb 5-8 g/dl. Komponen darah yang diberikan adalah PRC dengan tetesan lambat.
Pecegahan
Pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi anemia ialah mengonsumsi makan yang bergizi dan makanan kaya zat besi.